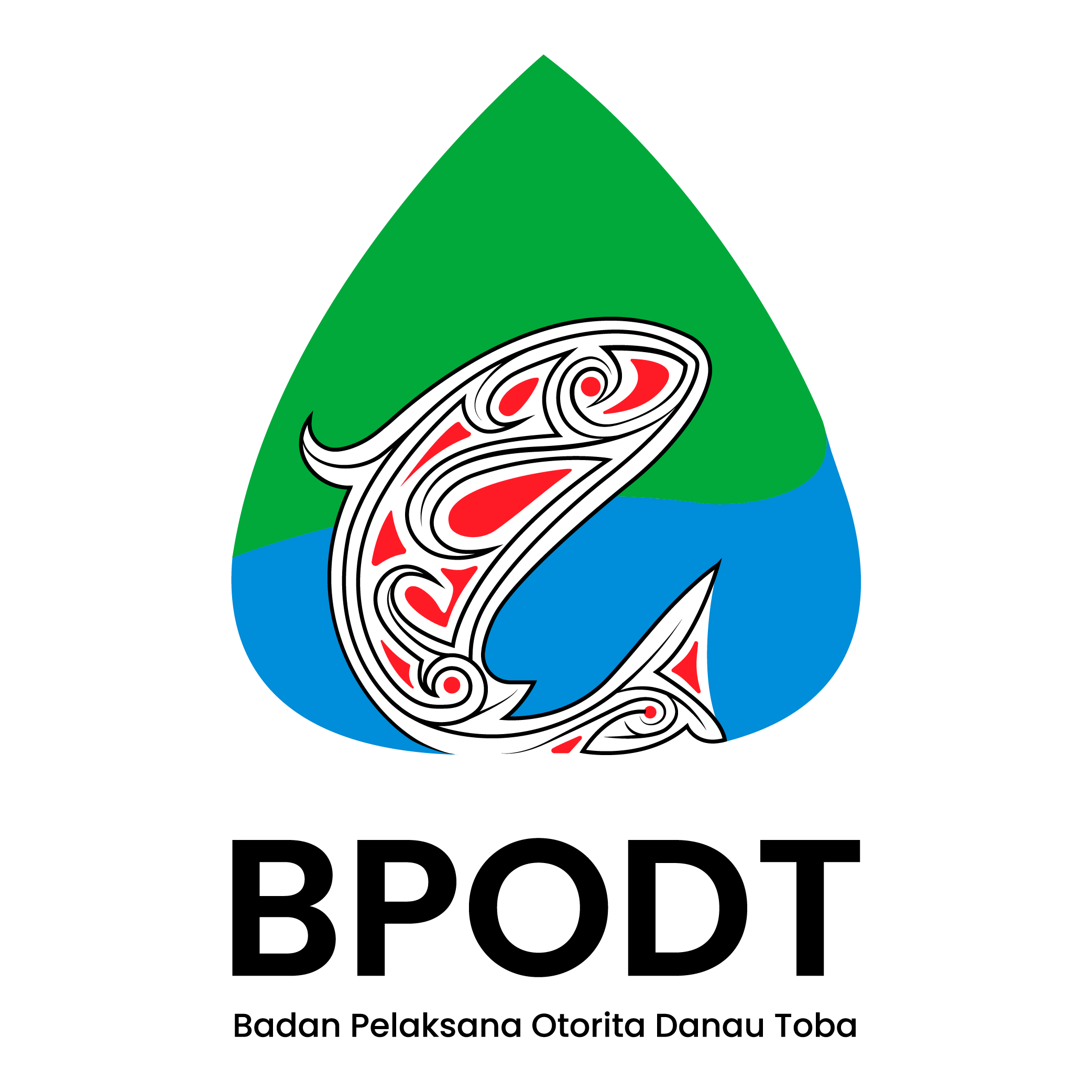Penulis dan Foto: Dinda Marley
Pohon Haminjon. (Dinda Marley)
Sesajen yang disajikan adalah itak gurgur dan na marmiak-miak. Dipersembahkan kepada roh leluhur dan penjaga tombak haminjon agar petani diberi hasil panen berlimpah dan kesehatan. Kemudian dengan hati tulus, santun dan sabar membujuk pohon bak merayu seorang gadis sambil bersenandung, “parung simardagul-dagul, sahali mamarung gok appang, gok bahul-bahul…“
——-
Ada legenda di Tano Marbun khususnya di Pandumaan dan Sipituhuta, sekarang masuk wilayah administrasi Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), hidup satu keluarga miskin yang punya anak perempuan berparas cantik. Sang ayah berhutang banyak kepada orang kaya di kampung dan tak mampu membayar sebab harta satu-satunya yang dimiliki hanya anak-anaknya.
Si orang kaya meminta kepada sang ayah agar menikahkan anak gadisnya sebagai penebus utang. Tak mau menikah dengan pria yang bukan pujaan hati, apalagi sudah seumuran ayahnya, sang putri yang tak diketahui namanya ini memilih lari dan bersembunyi ke hutan.
Dalam persembunyiannya, sang putri terus menangis memikirkan nasib dan keluarganya. Dia lalu berdoa kepada Mula Jadi Nabolon agar orangtuanya bisa membayar utang dan hidup senang. Lambat laun, tubuhnya berubah menyerupai pohon dan mengeluarkan getah putih seperti lelehan lilin.
Keluarga yang nyaris putus asa mencari, akhirnya menemukan anak yang hilang sudah berubah wujud menjadi pohon. Mereka lalu saling bertangis-tangisan. Sebelum berpisah, sang anak memberi bekal dan berpesan kata kepada ayahnya.
“Biar lunas utang mu, kasikan ini (sambil memberikan getah putih yang sudah mengkristal dari tubuhnya) sama orang kaya itu. Sedikit saja kau bawa ini, pasti lunas utang mu,” ucapnya.
Sang ayah menuruti ucapan anaknya, meski sepanjang jalan pulang, dia tak percaya. Besoknya, dia menemui orang kaya dan memberikan kristal putih yang memiliki wangi khas. Sang orang kaya terkejut dan bertanya dari mana dia mendapat haminjon tersebut.
“Utang mu lunas, tapi aku minta kau mengambil lagi getah ini,” kata orang kaya.
Ayah sang putri mengangguk dan kembali ke hutan untuk bertemu anaknya. Tapi dia tak menemukan apa-apa kecuali sebatang pohon bergetah putih tempat terakhir kali dia berjumpa putrinya. Waktu terus berjalan, pohon haminjon terus tumbuh dan bertebaran di Bumi Tapanuli. Para tetua mempercayai bahwa sang putri yang mendiami hutan-hutan dan memberi kekayaan dengan getah yang melimpah kepada petani.
“Ada orangtua di Pandumaan yang percaya, kalau dirinya sedang berada di hutan dan bermimpi didatangi anak gadis berpakaian putih, bersih dan cantik, besoknya atau pas panen pasti getahnya melimpah,” ucap Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak Roganda Simanjuntak pada Rabu malam, 18 November 2020.
Haminjon adalah kemenyan, istilah kimianya Styrax Benzoin atau sering juga disebut Olibanum. Para tetua Batak, pohon ini dianggap berkah Tuhan karena getahnya memberikan kesejahteraan. Bagi masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, selain dianggap simbol kesejahteraan juga sakral. Sampai sekarang, mereka masih melakukan ritual marhottas ketika memulai pekerjaan di tombak haminjon (hutan kemenyan), mulai dari manige (menyadap) sampai memanen.
Sesajen yang disajikan adalah itak gurgur (penganan dari tepung beras dan gula merah), na marmiak-miak (bisa daging babi dan telur ayam kampung. Dipersembahkan kepada roh leluhur dan penjaga tombak haminjon agar petani diberi hasil panen berlimpah dan kesehatan. Kemudian dengan hati tulus, santun dan sabar membujuk pohon bak merayu seorang gadis sambil bersenandung.
“Setelah martonggo (berdoa), kemudian itak dan daging dioleskan ke kemenyan dan bersenandung, ‘parung simardagul-dagul, sahali mamarung gok appang, gok bahul-bahul’” kata Ganda, begitu dia biasa dipanggil.
Menurutnya, tinggal para orangtua-orangtua Batak yang masih percaya dengan legenda Putri Haminjon, generasi muda kini sudah kurang. Pengaruh masuknya agama Kristen dan menganggap kemenyan hanya sebatas nilai ekonomis yang menggerus kesakralan dan spiritualis.
Sebelum agama Kristen masuk ke Tapanuli, kemenyan banyak digunakan masyarakat Batak untuk ritual menyembah sang penguasa alam raya. Asap pembakaran yang membubung tinggi menjadi representasi doa yang naik kepada Sang Pencipta. Tradisi Katolik dalam misa khusus menjadikan kemenyan bagian dari serbuk ratus yang dibakar dalam bara untuk mengepulkan asap beraroma. Di tanah Jawa dan banyak budaya di dunia percaya wangi kemenyan yang dibakar mampu mendatangkan juga mengusir roh.
“Salah satu yang sedang kami perjuangkan saat ini adalah mengembalikan kesakralan dan kejayaan haminjon itu,” ujarnya.
Kemenyan menjadi hasil bumi yang mahal, pada 1960-an di Humbahas. Harganya sama dengan emas. Para petani mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Surat kabar Imanuel yang diterbitkan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) edisi 24 Oktober 1920 menampilkan grafik hasil bumi yang dikeluarkan dari Tapanuli Utara pada 1919 didominasi oleh karet, kopi, kopra dan kemenyan.
Produksi kemenyan sebanyak 1,8 ton lebih dengan nilai jual 1,5 juta Gulden. Masih di surat kabar yang sama edisi 14 November 1920 dilaporkan, pedagang besar meraup untung besar dari kemenyan. Harga belinya 70 sen per kilogram dan dijual 2,22 Gulden.
Lewat Pelabuhan Barus, haminjon dibawa menjejak tanah Eropa hingga Timur Tengah. Bangsa Eropa sejak dulu mengenal Tano Batak sebagai penghasil kemenyan terbaik. Namun, meski perdagangan ini sudah berjalan ratusan tahun, petani tak bisa menentukan harga dan tak mengetahui harga di perdagangan dunia. Sejak dulu, mereka pasrah dengan nominal yang ditentukan tokke (pengepul). Mungkin mereka berpikir, dengan harga di tokke saja sudah kaya…
Duka di Tanah Leluhur
Kemenyan biasa tumbuh di daerah perbukitan dengan ketinggian 900-1.200 meter di atas permukaan laut, bersuhu antara 28-30 derajat Celsius. Berbeda dengan karet, penyadapan getah tak perlu wadah. Setelah dicungkil, getah akan keluar dari batang pohon, meleleh seperti lilin dan lengket di kulit pohon.
Cukilan pertama akan menghasilkan getah putih (sidukabi) yang baru bisa diambil sekitar tiga bulan kemudian. Getah menempel di kulit pohon sehingga harus mencongkel kulit pohon untuk memanennya. Getah ini dihargai paling tinggi, sekitar Rp 300.000-an per kilogram.
Getah haminjon mengalir di batangnya. Getah ini yang kemudian dijual dan harusnya berharga mahal. (Dinda Marley)
Bekas cukilan akan menghasilkan tetesan getah kedua yang disebut jurur, bisa dipanen dua sampai tiga bulan setelah memanen sidukabi. Setelah itu muncul getah ketiga yang disebut tahir, harganya lebih murah.
Haminjon Toba atau styrax sumatrana dan Haminjon Durame atau styrax benzoin dryand yang paling banyak tumbuh di Kabupaten Tapanuli Utara, Humbahas, Pakpak Barat, Toba dan Samosir. Juga dikembangkan di Dairi, Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah meski tidak terlalu banyak. Namun, tetap daerah penghasil terbesar masih dirajai Tapanuli Utara dan Humbahas.
“Lagi rendah harga kemenyan, di tingkat petani mereka jual ke tokke Rp 230.000 sampai 250.000 per kilogram yang kualitas nomor satu,” kata Roganda.
Adalah istilah para tokke untuk klasifikasi kemenyan yaitu arit bakat, samsam dan jurur. Roganda menjelaskan, arit bakat atau diarit maksudnya getah kemenyan dipisahkan dari kulit pohon. Samsam artinya percampuran getah yang kecil dan besar, harganya paling mahal Rp 200.000 per kilogram. Paling murah adalah jurur, bentuknya seperti serpihan atau sisa-sisa kikisan.
“Sebelum pandemi, harga sudah anjlok. Mungkin permainan tengkulak yang melakukan penimbunan,” ucapnya.
Bagi Ganda, haminjon adalah tanaman unik dan misteri. Hidupnya bergantung pada banyaknya pohon alam yang melindungi dari paparan langsung matahari, tanpa pelindung, satu tetes getah pun tak keluar. Tumpang tindih izin konsesi perusahaan seperti PT TPL ditambah yang terbaru, proyek pemerintah food estate), dan genjarnya perluasan alih fungsi hutan alam menjadi monokultur adalah jalan lempang punahnya kemenyan.
Komitmen pemerintah membangun wisata Danau Toba bertaraf internasional, harusnya menjadi peluang untuk melestarikan tombak haminjon karena sebaran hutannya merupakan sumber air untuk danau. Hutan kemenyan juga bisa dijadikan tujuan wisata ekologi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi semua izin yang tumpang tindih dengan hutan kemenyan, termasuk gencar mengakui hutan adat.
“Pemerintah harus menciptakan pasar yang adil bagi petani. Memfasilitasi mesin produksi untuk mengolah kemenyan supaya petani tidak lagi hanya menjual getah, dengan begitu akan memutus rantai tengkulak yang panjang,” katanya lugas.
“Petani langsung haminjon yang baru dipanennya ke tengkulak yang ada di setiap kampung atau desa. Kemudian menjualnya kembali ke tokke di Doloksanggul, biasanya ketika onan. Menurut Ganda, dari Doloksanggul langsung dikirim ke Jakarta atau Semarang, terus ke Singapura, terus entah ke mana-mana lagi. Maunya dia, petani yang terhubung langsung dengan pabrik atau penampung di Jakarta, Semarang, atau mana saja,” ungkapnya.
Ganda pernah bertemu seorang tokke di Jakarta, punya pabrik yang tak terlalu besar. Saat ditanya kenapa tidak membeli langsung ke petani, si tokke beralasan takut kewalahan di bahan baku kalau membuka sumber baru. Dirinya sudah nyaman dengan sumber lama yaitu para tengkulak besar.
“Kami bilang, kalau kalian menentukan misalnya dalam dua kali setahun bahan baku harus tersedia misalnya sepuluh ton, kami akan sanggupi,” kata Ganda.
Caranya dengan membentuk koperasi kemenyan di tiap. Misalnya di Sipituhuta da 700 petani, setengahnya wajib menjual haminjon ke koperasi. Harganya dibuat sedikit lebih tinggi dari harga pasar atau tokke kampung, belum lagi ditambah dari desa-desa lain, bisa memenuhi kuota bahan baku berapa pun yang diminta.
“Nah, jadi yang kami tangkap mereka sudah main lama dengan tengkulak-tengkulak itu. Kebanyakan orang Cina di Siantar dan Medan, itulah pemainnya, sama yang di Jakarta gitu…” ungkapnya.
Bersama para petani, AMAN Tano Batak pernah menghitung pendapatan langsung dan tidak langsung dari kemenyan. atu kabupaten diasumsikan sampai ratusan miliar penjualannya dalam setahun. Artinya, bisa diasumsikan uang yang tinggal di kampung atau kabupaten berapa puluh atau ratus miliar yang dibelanjakan memutar roda ekonomi. Ini yang belum di tangkap pemerintah kabupaten sebagai peluang.
“Misalnya pemkab membentuk perusahaan daerah yang yang menampung getah kemenyan dengan harga sedikit menandingi harga di tengkulak, pasti akan ke situ semua, walau hanya beda seribu aja pun… Tapi belum ada yang serius, kita sering aksi dan audensi dengan pemkab, seolah-olah malah ada anggapan bertani kemenyan sudah ketinggalan zaman, gak modren lagilah gitu,” ucapnya masygul.
Dia lalu bercerita, sebelas kampung anggota AMAN Tano Batak menggantungkan hidup sebagai penghasil kemenyan, tersebar di Humbahas, Taput dan Toba. Kini, sedang berjuang dari kehancuran sistemik akibat klaim Kementerian Kehutanan yang menyatakan tanah adat yang di dalamnya tombak haminjon sebagai kawasan hutan negara khususnya di daerah Humbahas. Pemerintah menerbitkan Hak Penguasaan Hutan/Tanaman Industri (HPH/TI) kepada perusahaan bubur kertas tanpa mempertimbangkan aspek historis, budaya, ekonomi masyarakat adat.
“Sebelum republik ini ada, masyarakat sudah hidup mandiri, berdaulat atas tanah dan hutan adatnya. Tidak tanggung-tanggung izin yang diberikan, puluhan ribu hektar tombak haminjon tiba-tiba masuk konsesi. Tombak haminjon disulap jadi hutan eucalyptus yang menjadi bahan baku pulp. Ribuan masyarakat adat kehilangan tanah dan mata pencaharian. Konflik berkepanjangan terjadi sampai hari ini, masyarakat harus menderita demi perjuangan mempertahankan tanah leluhur,” katanya dengan suara meninggi.
“Mereka dianggap penghambat investasi, melawan negara dan tidak taat hukum. Dipaksa mengemis untuk meminta tanah dan hutan adatnya kembali. Berkali-kali dikriminalisasi dan dibenturkan dengan aparat pemerintah,” sambung Ganda dengan suara bergetar.
Minimnya peran pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam pemasaran haminjon menyebabkan ketidakstabilan harga, memberi ruang tengkulak menguasai pasar mulai kampung sampai ke pembeli terakhir. Ini juga yang menyebabkan kaum muda tak tertarik menjadi petani karena kemenyan tidak menjanjikan seperti dahulu. Mereka lebih memilih pekerjaan lain atau merantau.
1980-an, adalah tahun dimulainya petani menjual hasil panennya dengan harga murah. Getah yang mengandung asam sinamat sekitar 36,5 persen sehingga banyak digunakan industri farmasi, kosmetik, rokok dan obat-obatan ini merosot jauh di bawah emas. Petani juga merasakan hasil panennya terus menurun, tokke-tokke berkurang. Para petani di Kecamatan Pollung sejak lima tahun lalu sudah mengatakan haminjon berakhir masa jayanya.
“Tanpa ada solusi konkrit oleh semua pihak, kita prediksi haminjon sian Tano Batak punah beberapa tahun lagi. Pemerintah harus menyelamatkannya, keluarkan tombak haminjon dari areal konsesi dan kawasan hutan negara. Olahan jadi kemenyan harus diciptakan di dalam negeri, apalagi kalau petani dapat melakukannya sendiri di kampung, sehingga keuntungan benar-benar dirasakan petani,” nada suara Ganda naik lagi.
“Kita tidak ingin masa kejayaan haminjon berlalu begitu saja, atau sekedar cerita sukses para leluhur. Kita juga tidak ingin kemenyan punah karena manfaatnya sangat banyak, khususnya bagi petani di Tanah Batak. Mari kita selamatkan haminjon. Horas!” katanya menutup percakapan.
“Kalau Dulu, Kaya Kami Dibuat Haminjon Ini…”
Ribuan petani hamijon menggantungkan hidupnya dari memanen getah berbau khas ini, turun-temurun, bahkan sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Harri Lumbangaol, warga Desa Matiti, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbahas mengatakan, dari kemenyan-lah dia dan keluarganya hidup. Meski harganya tidak lagi seperti dulu.
“Kalau dulu, kaya kami dibuat haminjon ini. Sekarang, cukup makan saja, tapi tak apa yang penting tak mau kami tebang pohonnya,” kata ayah dua anak itu.
Opung Solin, warga Desa Karing, Kabupaten Dairi juga mengatakan seperti ucapan Harri. Baginya kemenyan masih memberi harapan untuk membantu ekonomi keluarga. Walau komoditi lain datang menawarkan kepraktisan dan efesiensi, juga harga jual yang lebih mahal, laki-laki ramah ini masih asyik mengurus tombak haminjonnya.

Pohon haminjon menjulang tinggi. (Dinda Marley)
“Samaku, ini harta yang harus dipertahankan. Biarlah anak-anak sekarang tak mau lagi berladang kemenyan. Kami yang tua-tua ini masih sanggup mengurusnya. Apalagi, panjang jalan kami mempertahankan kemenyan ini, banyak sudah perjuangan yang kami lakukan,” katanya mengenang.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK Djati Witjaksono Hadi pada 4 Februari 2020 mengeluarkan siaran pers. Isinya, berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 yang menyebut di 2018 luas tanaman kemenyan di Provinsi Sumut adalah 23.068 hektare dengan produksi getah sebanyak 8,3 ton. Potensi pasar yang dapat diraih dengan produksi tersebut mencapai Rp 2,08 triliun per tahun.
”Bayangkan, jika rata-rata harga kemenyan di lokal saja Rp 250.000 per kilogram, dengan produksi getah 8,3 ton lebih, maka nilai perdagangan yang dicapai Rp 2,08 triliun per tahun. Ini nilai yang besar dan sangat ekonomis,” kata Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Aek Nauli Pratiara ketika menjadi pemantik diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Potensi dan Kondisi Komoditas Ekspor Unggulan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Humbahas”.
FGD diselenggarakan Ketua Panitia Kerja Perdagangan Komoditas Ekspor yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung bekerja sama dengan Pemkab Humbahas, awal Februari 2020 di ruang rapat kantor bupati Humbahas. Hadir direktur jenderal pengembangan ekspor nasional Kemendag, Sekda Humbahas, anggota DPRD Humbahas dan perwakilan petani.
Berbalik dengan keluhan para petani, menurut mereka, produksi kemenyan di Sumut cenderung meningkat setiap tahun akibat terus meningkatnya luasan tanam pohon. Data BPS menyebut, pada 2016 luas tanaman 22.902 hektare dengan produksi getah 5,0 ton, di 2017 luas tanaman menjadi 22.912 hektare dengan produksi getah 6,1 ton, sehingga di 2018 luasan tanam naik lagi mencapai 23.068 hektare dengan produksi getah 8,3 ton.
Namun untungan tidak sepenuhnya dirasakan petani. Pratiara bilang, meski harga kemenyan di pasar internasional tidak pernah turun, cenderung tinggi dan stabil, tapi harga di tingkat petani terlalu rendah. Menurutnya perlu diatur skema perdagangan supaya selisih harga di level petani dan internasional seimbang.
“Skema ini bertujuan melindungi petani yang memproduksi kemenyan sehingga mendapatkan harga dan nilai ekonomis yang tinggi. Ketika itu terwujud, dampak positif yang diharapkan Presiden Jokowi tentang peningkatan pendapatan perkapita di masyarakat bisa terjadi,” pungkas Pratiara.
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor yang hadir dalam FGD tersebut membenarkan selisih harga yang sangat jomplang. Menurutnya, jauhnya selisih harga disebabkan lemahnya tata niaga dan rendahnya produktivitas kemenyan. Antara lain disebabkan terbatasnya akses informasi pasar maupun teknologi.
“Kelembagaan petani dengan jalinan kemitraan sangat lemah dan mata rantai perdagangan terlalu panjang,” kata Dosmar.
Menanggapi semua ini, Martin Manurung mengatakan kalau keadaan tidak bisa dibiarkan berlarut, harus dicari solusi. Menurutnya perlu kerja sama antar instansi dan pemerintah mulai daerah sampai pusat. Soal perdagangan kemenyan, dibawanya ke Jakarta untuk dibahas dalam rapat panja.
“Kita harus cari solusi, kalau tidak, bisa dibayangkan sepuluh atau 20 tahun kedepan kita tidak akan punya lagi komoditas ini. Secara ekonomi wajar petani kemenyan beralih ke komoditas lain karena nilai ekonomisnya tidak berimbang bahkan kecil,” kata Martin.
Marandus Sirait, pemilik Taman Eden 100 di Desa Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba mengatakan, kemenyan adalah komoditi yang mahal. Harganya lebih tinggi dari kopi karena tertentu pasarnya. Banyak orang tidak mengetahui ke mana harus menjual sehingga mulai enggan menanamnya.
“Kalau haminjon itu, jaranglah murah…” ucapnya membuka percakapan.
Haminjon hanya tumbuh di daerah-daerah tertenju saja, salah satunya di Humbahas, kata Marandus. Selain harus hidup berdampingan dengan pohon pelindung, getahnya baru bisa dipanen saat pohon berumur sepuluh tahunan.
Selama proses memanen, para lelaki menginap beberapa hari di hutan, mengumpulkan sedikit demi sedikit getah sadapan. Anak-anak muda mulai malas mengerjakannya, tinggallah tangan-tangan keriput yang bertahan, mencungkil tiap pohon dengan cinta.
“Kalau di Toba ini, jarang orang mau mengerjakan yang sulit prosesnya. Makanya orang Toba jarang mau membuat produk-produk UMKM, sekarang baru mau kita gerakkan, saya pun gak tau kenapa…” tutur Marandus.
Ditanya apakah keengganan tersebut karakter suku, ketua asosiasi UMKM Sumut wilayah kawasan Danau Toba ini sulit menjawabnya.
“Satu sisi, belum banyak orang Batak di Toba ini melihat pelaku UKM yang banyak duit sehinga dianggap sepele. Misalnya, belum pernah dilihatnya membuat keripik, kerupuk jangek, keripik singkong yang murah-murah tapi berton-ton setiap minggu. Begitu juga dengan haminjon…” ucapnya sambil mengajak meninggalkan lokasi.
Taman Eden 100 mirip Kebun Raya Bogor. Di lahan seluas 40-an hektare ini, ditanami ratusan jenis pohon, dari yang sering ditemui sampai yang benar-benar langka. Menjadi salah satu ekowisata yang baiknya dikunjungi saat berada di Danau Toba dari sisi Parapat, Kabupaten Simalungun atau Balige di Kabupaten Toba.
“Di sini juga ditanam haminjon, tapi tidak untuk dideres, hanya untuk objek penelitian saja…” tutupnya.
1,444 total views